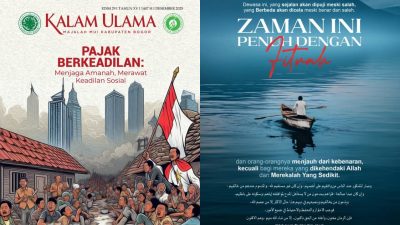MUI-BOGOR.ORG – Sukaraja – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor menggelar perkuliahan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Angkatan XIX pada Sabtu, 19 Juli 2025, di Balai Diklat Dharmais, Kecamatan Sukaraja. Perkuliahan pada minggu ketiga ini menghadirkan Sejarawan Bogor, Hendra M. Astari, yang menjelaskan sejarah peradaban sunda dan penyebaran Islam di Kabupaten Bogor.
Dalam pemaparannya, Kang Hendra mengajak para peserta PKU menelusuri jejak peradaban manusia di Tatar Sunda, mulai dari masa pra-sejarah hingga masa perkembangan Islam di wilayah Bogor. Ia menjelaskan bahwa bukti adanya peradaban awal dapat ditelusuri melalui sumber sejarah primer seperti artefak, naskah, dan situs-situs arkeologi.
Salah satu wilayah yang memiliki sumber sejarah penting di Kabupaten Bogor adalah Kecamatan Cibungbulang, di sana terdapat Situs Pasir Angin sejenis batu monolit yang telah diteliti para arkeolog yang diperkirakan berusia sekitar 3.000 tahun berdasarkan uji karbon (carbon dating C14).

“Jika ada yang bertanya sejak kapan manusia menghuni Tatar Sunda Bogor, maka penelitian terhadap batu tersebut bisa menjadi jawaban yang konkret,” jelas Hendra.
Terkait sejarah masuknya Islam ke wilayah Sunda khususnya Bogor, Hendra menjelaskan bahwa proses Islamisasi dimulai dari dakwah Walisongo, khususnya melalui Sunan Gunung Jati dari Kerajaan Demak yang menyebarkan Islam ke Banten tahun 1522 dan ke Sunda Kalapa tahun 1527.
Penyebaran Islam terus meluas sampai ke pesisir pantai utara lalu ke daerah Jawa Tengah, hingga mulai masuk ke daerah pedalaman, dari utara ke selatan, sampai akhirnya masuk ke Bogor.
Namun, Hendra menyatakan bahwa klaim penyebaran Islam pada masa Kerajaan Sunda Pajajaran masih memerlukan bukti lebih lanjut. Sekalipun dalam naskah Carita Parahyangan disebutkan, bahwa keruntuhan Kerajaan Sunda Pajajaran salah satunya disebabkan karena banyaknya penduduk yang sudah memeluk Islam.
“Sepanjang penelitian saya, belum ditemukan peninggalan peradaban Islam pada masa Kerajaan Sunda Pajajaran. Jika kelak ditemukan, maka tentu kesimpulan saya akan berubah,” ujarnya.
Ia juga menyebut sejumlah bukti sejarah Islam di Bogor yang berasal dari periode 1780 hingga 1945, baik berupa manuskrip maupun bangunan bersejarah. Di antaranya adalah naskah silsilah tarekat Syattariyah, makam Garisul Jasinga (1820), naskah Citereup, manuskrip Al-Qur’an Bantar Jati di Kemang, serta bangunan seperti Masjid Agung Empang, Pondok Pesantren Al-Falak Pagentongan, dan Pesantren Bakom.
Lebih jauh Kang Hendra menjelaskan, ketika Kerajaan Banten berkonflik dengan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai salah satu raja yang paling gigih melawan kekuasaan VOC, meskipun akhirnya ditangkap dan menyerah pada tahun 1682.
Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 17 April 1684, disepakati sebuah perjanjian baru antara Banten dan VOC, yang di antaranya menyebutkan bahwa wilayah di sebelah timur Sungai Cisadane berada di bawah kendali VOC, sedangkan bagian baratnya tetap menjadi wilayah Kerajaan Banten.
Usai kesepakatan tersebut, pada tahun 1687, VOC mengirimkan ekspedisi pertamanya dari Batavia menuju Bogor dan terus ke selatan, yang dipimpin oleh Sersan Schipio.
Menurut Kang Hendra, masih banyak aspek sejarah lokal yang perlu digali dan diteliti secara lebih serius. Ia berharap generasi muda, khususnya para kader ulama MUI Kabupaten Bogor, memiliki kesadaran sejarah agar dapat memperkuat jati diri keislaman dan kebangsaan. (fw)