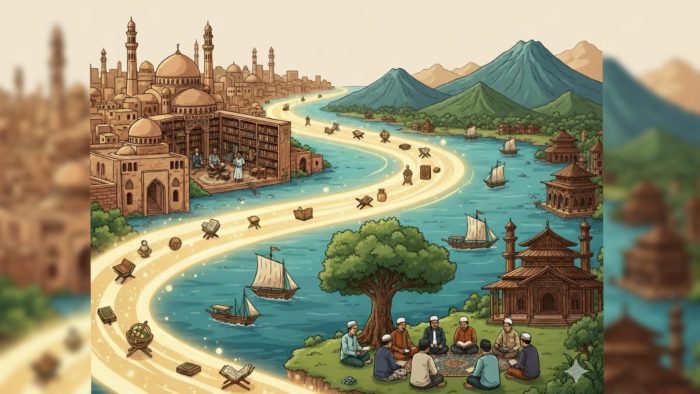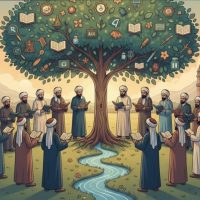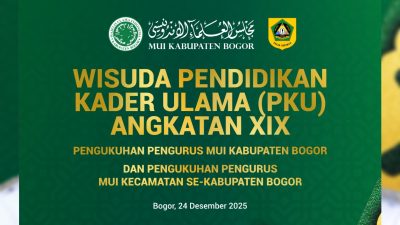MUI-BOGOR.ORG – Selama ini kata mazhab lebih sering dikaitkan dengan fikih. Namun, ternyata dalam filsafat Islam juga lahir berbagai mazhab pemikiran. Berdasarkan periode kemunculannya, ada empat mazhab besar yang pernah muncul dan berkembang, yaitu mazhab Paripatetik (Masyâiyyah), Iluminasi (Isyrâqî), Teosofi-Transendental (al-Hikmah al-Muta’âlîyah), dan ‘Irfani (Qusûf). Keempat mazhab ini kemudian terbagi menjadi dua kategori besar, dua di antaranya berkembang di kalangan Sunni, sementara dua lainnya tumbuh subur di kalangan Syiah.
Demikian dilontarkan oleh seorang Ahli Filsafat Islam, Dr. (C) Puad Hasan, MA., dalam forum Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI Kabupaten Bogor Angkatan XIX yang diselenggarakan di Aula Balai Diklat Dharmais, Kecamatan Sukaraja, Sabtu malam (13/9/2025). Pada forum tersebut, pria yang selama mondoknya akrab disapa Mang Hes, menjabarkan dua mazhab filsafat Islam yang termasuk sunni, yaitu paripatetik (Masyâiyyah) dan ‘irfani (Qusûf).

Mazhab Filsafat Islam Paripatetik (Masyâiyyah)
Mazhab Filsafat Islam Paripatetik adalah aliran filsafat yang banyak dipengaruhi logika Aristoteles. Istilah Paripatetik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti “berjalan-jalan.” Nama ini diambil dari kebiasaan Aristoteles dan gurunya, Plato, yang sering mengajar sambil berjalan bersama murid-muridnya.
Ciri khas mazhab ini adalah sifatnya yang diskursif. Artinya, setiap gagasan selalu dibangun melalui argumen, kemudian diuji dengan proposisi dan bantahan. Dari sini lahir tradisi berpikir kritis yang kelak banyak memengaruhi perkembangan filsafat Islam.
Salah satu tokoh besar dalam mazhab filsafat Paripatetik adalah Al-Kindi. Ia dikenal sebagai filsuf Islam pertama yang membuka pintu bagi masuknya ilmu pengetahuan dari luar. Bersama Hunain bin Ishaq, Al-Kindi terlibat dalam proyek besar penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, hingga India. Bedanya, Hunain lebih banyak menerjemahkan karya-karya umum, sementara Al-Kindi fokus pada bidang filsafat, metafisika, dan teologi. Dari sinilah tradisi intelektual Islam semakin berkembang dan kaya dengan berbagai khazanah ilmu.

Selain Al-Kindi, lahir pula filsuf besar Islam lainnya, yaitu Al-Farabi. Ia dikenal dengan sebutan al-Mu’allim al-Tsâni (Guru Kedua), sedangkan al-Mu’allim al-Awwal (Guru Pertama) adalah Aristoteles. Salah satu pemikiran Al-Farabi yang terkenal adalah filsafat musik. Menurutnya, segala bunyi indah yang kita dengar di dunia ini tidak ada artinya bila dibandingkan dengan suara alam semesta.
Dalam filsafat musik, kata Kang Puad, ada sebuah ungkapan menarik, bahwa alam semesta ini terus berputar layaknya sedang bertawaf. Dari putaran itu lahirlah suara yang amat indah, tak tertandingi oleh apa pun. Suara tersebut dapat dirasakan pada sepertiga malam terakhir. “Seperti apa suaranya? Itu hanya bisa dirasakan di sepertiga malam,” tuturnya.
Bergeser ke pemikiran filsuf Islam lain, yaitu Ibnu Sina yang pengaruhnya meluas hampir ke seluruh dunia, bahkan menjadi tokoh puncak dalam mazhab filsafat paripatetik. Karya monumentalnya di bidang kedokteran adalah al-Qânun fi al-Thib, sebuah kitab yang hingga kini masih dijadikan rujukan penting di berbagai fakultas kedokteran dan kesehatan di banyak negara.
Pemikiran Ibnu Sina juga sangat berpengaruh, khususnya terhadap ilmu kalam. Ia dikenal dengan argumennya tentang Dalil al-Imkan untuk membuktikan keberadaan Tuhan, dengan istilah-istilah seperti wujud mumkin, wujud jaiz, wujud mustahil, dan wujud wajib. Pemikiran rasional ini banyak diadopsi dan digunakan oleh para ulama Sunni.
Setelah Al Kindi, Al Farabi, dan Ibnu Sina, jangan lupakan juga filsuf Islam yang satu ini, yaitu Ibnu Rusyd. Ia merupakan filsuf terakhir yang pemikirannya berpengaruh di dalam aliran filsafat paripatetik.
Setelah pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tahun 1258 M menghancurkan Dinasti Abbasiyah di Baghdad, mereka membakar kota, menjarah, dan membantai penduduknya, serta menghancurkan bangunan-bangunan penting seperti masjid, perpustakaan, dan istana, bahkan membuang ribuan buku ke Sungai Tigris, perkembangan filsafat Islam di kalangan Sunni nyaris terhenti pasca wafatnya Ibnu Rusyd.
Namun, di kalangan Syiah justru filsafat terus tumbuh dan menemukan ruang baru. Dari sanalah lahir dua aliran besar yang banyak dipengaruhi para pemikir Persia, yakni filsafat Iluminasi (Isyrâqî) dan filsafat teosofi-transenden (al-Hikmah al-Muta‘âlîyah).
Kemudian, apakah filsafat di kalangan sunni benar-benar mati? Tentu saja tidak. “Filsafat di kalangan sunni tidak seutuhnya mati, saya cukup lama mengkaji ini,” tegas Kang Puad kepada para mahasiswa PKU 19.
Kandidat Doktor Pemikiran Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut kemudian menjelaskan, salah satu tokoh besar yang berperan dalam lahirnya mazhab filsafat di kalangan Sunni adalah Fakhruddin al-Razi. Dari muridnya, Al-Abhari, lahir sebuah karya penting berjudul Hikmah al-‘Ain. Kitab ini kemudian disyarahi oleh Mulla Sadra dan menjadi rujukan utama dalam filsafat Teosofi-Transendental.
Pemikiran Mulla Sadra itu lalu diteruskan oleh Nasiruddin al-Tusi, salah satu tokoh penting dalam aliran Iluminasi. Sementara murid Fakhruddin lainnya, al-Mawardi, menulis kitab al-Risalah al-Syamsiyyah yang juga ikut memperkaya khazanah keilmuan.
Dari sinilah muncul cikal bakal filsafat Islam di kalangan Sunni. Hanya saja, seiring waktu bentuknya lebih banyak berkembang ke arah filsafat tasawuf, yang kemudian menjadi ciri khas filsafat Islam mazhab Irfani.
“Karena itu, bisa dipahami bahwa filsafat Islam di kalangan Syiah maupun Sunni sejatinya memiliki inti yang sama. Yang membedakan hanyalah jalur sanad keilmuannya,” beber Kang Puad.
Mazhab Filsafat Islam ‘Irfani (Qusûf)
Mazhab filsafat Islam berikutnya adalah mazhab ‘Irfani atau Qusûf, yang lebih dikenal dengan istilah tasawuf falsafi. Ciri khas mazhab ini adalah memadukan ajaran tasawuf dengan kajian filosofis, sehingga pengalaman mistik dipahami secara rasional.
Sejumlah tokoh besar lahir dari mazhab ini. Sebut saja Ibnu Arabi dengan teori wahdatul wujud, al-Jiili dengan konsep Insan Kamil, al-Hallaj dengan gagasan al-Funun, Abu Yazid al-Busthami dengan teori al-Ittihad, hingga sosok masyhur Syekh Abdul Qadir al-Jailani.
Di Nusantara, pemikiran ini berkembang subur. Syekh Siti Jenar menjadi salah satu tokoh penting, bahkan di Sumatera hampir semua ulama abad ke-16 berdiri pada mazhab tasawuf falsafi. “Hampir semua ulama abad ke-16 di Sumatera memiliki pemikiran tasawuf falsafi,” jelas Puad Hasan.
Tokoh besar lain adalah Hamzah Fansuri, penyair hebat Nusantara yang menulis karya fenomenal Syair Ikan Tongkol. Syair ini menggambarkan bagaimana alam semesta menyatu dengan Sang Pencipta. Muridnya, Syamsuddin al-Sumatrani, juga menjadi filsuf penting yang melanjutkan tradisi ini. Dari keduanya, lahirlah generasi baru yang terus mengembangkan filsafat tasawuf di Nusantara.
Keempat mazhab filsafat Islam di atas pada dasarnya masih bersifat spekulatif, karena banyak membahas persoalan metafisika seperti jiwa, surga, hingga neraka. Namun, memasuki era modern, tema filsafat mulai bergeser. Filsafat tidak lagi hanya berkutat pada hal-hal metafisik, melainkan berkembang ke ranah yang lebih nyata seperti humanisme, kolonialisme, serta persoalan sosial dan politik.
Menutup perkuliahan, Kang Puad menekankan pentingnya sikap aktif dalam berkeyakinan. Menurutnya, keyakinan saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan nyata. Ia mencontohkan, filsafat bukanlah sekadar produk pemikiran, melainkan sebuah metode berpikir. Pertanyaannya kemudian, apa yang bisa kita lakukan dengan pengetahuan tersebut? Karena itu, lanjutnya, setiap orang perlu bergerak dan berbuat sesuai dengan apa yang diyakini.
Penulis: Siti Masitoh
Editor: Faisal