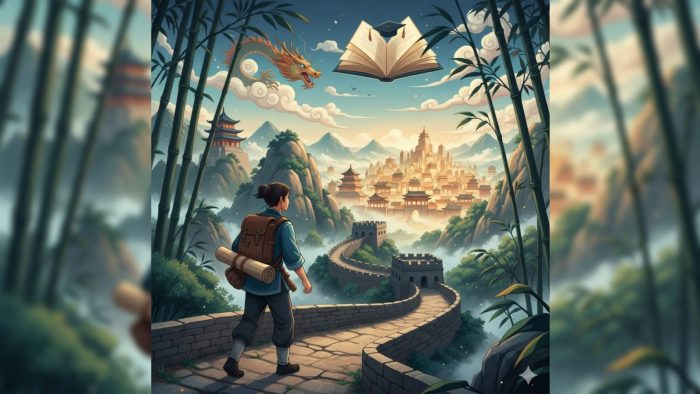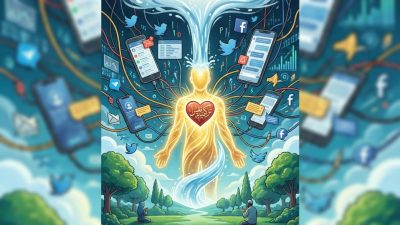MUI-BOGOR.ORG – Dalam dunia Islam sudah dikenal semangat keilmuan yang melintasi batas geografi, bahkan melalui medan yang sulit dan jarak yang jauh. Salah satu ekspresi motivasional yang sangat populer dalam Islam adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ, meski keabsahannya disangsikan, yaitu
اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْ باِلصِّيْنِ
“Carilah ilmu walau sampai ke Negeri China.”
Secara historis dan arkeologis, Tiongkok (China) memang layak disebut sebagai salah satu peradaban tertua di dunia. Menurut para arkeolog, peradaban China sudah ada sejak Dinasti Xia pada 2070 SM. Data kontemporer dari World Population Review menunjukkan bahwa China saat ini dihuni oleh sekitar 1,42 miliar jiwa.
Angka ini menjadikannya negara dengan populasi terbanyak kedua setelah India. Dari jumlah itu, sekitar 25 juta jiwa adalah Muslim, atau sekitar 1,8 persen dari total populasi. Mereka tersebar di berbagai provinsi seperti Xinjiang, Ningxia, Yunnan, dan Henan.
Sejumlah catatan sejarah menyebutkan bahwa Islam sudah masuk ke China sejak masa sahabat Nabi ﷺ, seperti Saad bin Abi Waqqash, yang diyakini ikut menyebarkan Islam ke wilayah Guangzhou pada abad ke-7.
Namun, dari sudut pandang geografis dan logistik, menuntut ilmu ke China dari jazirah Arab jelas bukan hal yang mudah. Jarak antara Makkah dan Beijing sekitar 7.670 kilometer.
Saat ini pun, perjalanan udara dari Makkah ke China membutuhkan waktu tempuh lebih dari 13 jam. Bandingkan dengan perjalanan dari Makkah ke Mesir yang hanya sekitar 2-3 jam menggunakan pesawat, atau bahkan ke Yaman melalui jalur darat yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15-20 jam.
Pertanyaan yang muncul sekarang yakni mengapa Nabi ﷺ tidak menyebut Mesir atau Yaman sebagai tujuan belajar, melainkan China?
Imam Abdullah al-Haddad memberikan penjelasan penting dalam an-Naṣāʾiḥ ad-Dīniyyah wa al-Waṣāyā al-Īmāniyyah, bahwa makna dari hadits ini tidak terletak pada literal geografisnya, melainkan pada semangat dan totalitas dalam menuntut ilmu.
China pada masa itu dikenal sebagai wilayah yang sangat jauh, sukar dijangkau, dan hanya sedikit yang mampu menempuhnya:
“والصين إقليم بعيد من أبعد المواضع، وقليل من الناس الذي يصل إليه لبعده. فإذا وجب على المسلم أن يطلب العلم وإن كان في هذا المحل البعيد، فكيف لا يجب عليه إذا كان بين العلماء ولا يلحقه في طلبه كثير مؤنة، ولا كبير مشقة؟”
“China adalah negeri yang sangat jauh, termasuk tempat yang paling sulit dijangkau, dan hanya sedikit orang yang bisa sampai ke sana karena jauhnya. Jika seorang Muslim tetap diwajibkan mencari ilmu meskipun letaknya sejauh itu, maka bagaimana mungkin ia tidak diwajibkan menuntut ilmu saat berada di tengah-tengah para ulama, tanpa banyak biaya dan tanpa kesulitan?” (Dar al-Hawi, 1999, hal. 91)
Dengan demikian, maqālah tersebut adalah bentuk majaz (metafora motivasional) yang menunjukkan bahwa Islam menghargai pencarian ilmu meskipun menuntut usaha besar, bahkan jika harus merantau ke tempat sejauh China.
Ini sejalan dengan prinsip universal Islam bahwa ilmu bisa dan harus dicari di mana saja, selama ia mengantarkan kepada kemaslahatan dan pemahaman yang benar tentang agama dan dunia.
China saat ini memang dikenal sebagai negara maju dalam bidang teknologi, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonominya. Beberapa lembaga global seperti IMF dan World Bank menempatkan China sebagai ekonomi terbesar kedua dunia.
Namun jika yang dimaksud adalah ilmu-ilmu agama Islam, maka pusat-pusat otoritatifnya masih berada di negara-negara dengan mayoritas Muslim dan tradisi pendidikan Islam yang mapan seperti Al-Azhar (Mesir), Universitas Islam Madinah (Arab Saudi), Jami’ah al-Qur’an (Sudan), IIUI (Pakistan), dan kampus-kampus Turki serta Iran.
Maka, menafsirkan adagium “carilah ilmu sampai ke negeri China” secara literal tanpa konteks adalah bentuk penyempitan makna. Frasa itu adalah simbol komitmen, bukan arahan geografis. Hadits ini mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seseorang harus siap menempuh jarak, waktu, rintangan, bahkan berpisah dari keluarga dan kenyamanan.
Dalam semangat itu, perjalanan belajar di negeri mana pun, termasuk China, tetap dapat menjadi bagian dari jihad keilmuan, selama ia dilakukan dengan niat ikhlas, tujuan mulia, dan bimbingan dari para guru yang mumpuni. Sebab ilmu yang dituntut dalam Islam adalah yang yuntafa’u bihi—yang mendatangkan manfaat: bagi diri, masyarakat, dan kemanusiaan.
Penulis: KH Abdul Muiz Ali, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat.