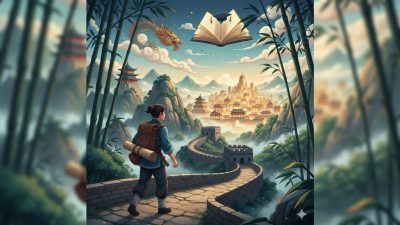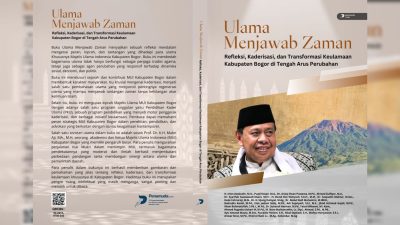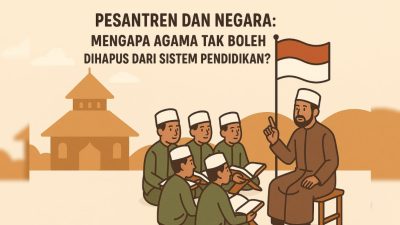MUI-BOGOR.ORG – Kebijaksanaan tidak hanya datang dari menara gading semata, ia juga bisa berasal dari perbincangan akrab kalangan biasa namun tercerahkan nan jauh di pelosok. Ada sebuah cerita yang menggambarkan hal ini dengan indah, tentang pencarian makna hidup oleh seorang ayah dan anaknya dari keluarga berada yang tinggal di kota. Cerita mana berasal dari buku berjudul “Ketika Pohon Bersujud” yang ditulis Achmad Siddik Thoha tahun 2011.
Di suatu sore yang teduh, keduanya, ayah dan anak menyusuri jalanan pedesaan yang cukup terpencil. Perjalanan mereka bukan sekadar wisata, melainkan pencarian makna hidup yang seakan hilang di tengah gemerlapan kota. Hingga akhirnya mereka berhenti di desa yang jauh dari keramaian. Pemandangan alami desa itu, dengan ladang hijau dan kicauan burung, menarik perhatian mereka, terutama perkampungan yang masih banyak pepohonannya.
Di tengah ketenangan itu, terjadilah percakapan bermakna antara ayah dan anak. Sang ayah bertanya apakah anaknya senang dengan perjalanan itu. Sang anak menjawab dengan semangat bahwa itu adalah perjalanan paling berkesan. Sang ayah menanyakan alasannya. Sang anak perlahan menjawab bahwa ia terkesan dengan pohon-pohon dan penduduk desa yang merawatnya, mengatakan mereka lebih kaya. Ia menunjuk pada pohon, kebun, air sungai, dan udara segar yang dimiliki warga desa, semuanya tersedia tanpa harus dibeli.
Anak itu selanjutnya mengatakan bahwa orang kota memerlukan kendaraan mewah dan AC, sementara penduduk desa terlindungi oleh pohon, memiliki udara segar, dan burung-burung datang dengan sendirinya. Ia juga menambahkan bahwa keluarganya membeli buah-buahan, rempah, dan obat, sedangkan penduduk desa memetiknya dari kebun sendiri. Sang ayah mengangguk tanda mengiyakan.
Sang anak kemudian menyatakan bahwa orang kota juga membeli kayu mahal dan memagari rumah untuk keamanan, sementara penduduk desa mendapatkan kayu gratis dan dilindungi pepohonan. Terakhir, ia menyatakan bahwa keluarganya mengeluarkan biaya untuk minum dan mandi, sementara penduduk desa bebas mengambil air dari sungai, dan keluarganya harus menabung untuk melihat pohon-pohon yang dinikmati penduduk desa setiap saat. Ayahnya tersenyum, puas dengan jawaban anaknya.
Pernyataan itu memantik kesadaran. Kesejahteraan, yang selama ini dibayangkan sebagai deretan angka, kendaraan mewah, fasilitas wah dan rumah besar, ternyata bisa hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan. Di balik kesederhanaan hidup di desa, tersimpan kemakmuran dalam bentuk yang lebih mendalam seperti rasa cukup, rasa terhubung dengan alam, serta jalinan sosial yang hangat. Meski cerita ini sekadar rekaan, ia sejatinya merupakan cermin dari realitas yang sering luput kita perhatikan.
Temuan dari studi global yang dilakukan Universitas Harvard memperkuat hal ini. Survei terhadap lebih dari 200 ribu orang di 22 negara menunjukkan bahwa Indonesia unggul dalam lima domain kesejahteraan sejati: kebahagiaan, kesehatan, makna hidup, karakter, dan hubungan sosial. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang unggul secara materi, justru tertinggal dalam aspek-aspek ini.
Meskipun ini kelihatanya lebih dari sekedar fiksi, tapi itulah sesungguhnya yang terjadi. Temuan tersebut nyata dipublikasikan dalam jurnal Nature Mental Health, berjudul “The Global Flourishing Study: Study Profile and Initial Results on Flourishing.” Dirilis 30 April 2025. Peneliti juga sebenarnya mengaku cukup kaget dengan hasil studi ini. Tyler VanderWeele, Professor of Epidemiology di Harvard TH Chan School of Public Health yang menjadi ketua riset mengatakan studi ini menawarkan bukti kuat jika kondisi keuangan semata tidak menjamin kemakmuran. Sebagaimana kata “flourishing” yang menjadi variabel utama penelitian, merupakan kata lain dari kehidupan bermakna dan kepuasan hidup yang relate dengan dukungan sosial setempat.
Namun bila kita merujuk pada kekayaan laten luar biasa, ada benarnya jika kita menyebut Indonesia sebagai negeri dengan “modal sosial” sangat besar. Gotong royong, arisan, pengajian, dan budaya membantu tetangga masih banyak bertahan di desa-desa. Semua ini menyumbang pada rasa dimiliki, dicintai, dan bermakna, sebagai komponen utama kesejahteraan menurut studi tersebut.
Lihat saja Desa Kutuh di Bali. Dengan mengembangkan wisata berbasis potensi lokal seperti Pantai Pandawa dan Gunung Payung, desa ini berhasil meraup pendapatan hingga Rp. 50 miliar per tahun (www.wartadesaku.id. 2024). Atau Desa Ponggok di Klaten, yang bertransformasi dari desa tertinggal menjadi desa maju dengan pendapatan Rp. 80 juta menjadi Rp. 3,9 miliar per tahun (www.sriwidadi.simsa.id. 2025). Namun, nilai utama dari kisah desa sejahtera bukan hanya berkisar di angka. Melainkan ketika mereka tetap menjaga harmoni dengan alam, melestarikan budaya, dan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukannya sekedar objek pasif.
Mungkin inilah waktunya kita memikirkan kembali makna kesejahteraan. Ia bukan sekadar tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup, kepada siapa kita terhubung, dan seberapa dalam kita merasa hidup itu sendiri bermakna. Ini sesungguhnya berbicara tentang rasa syukur, yaitu kemampuan untuk melihat kecukupan dalam apa yang sudah ada, dan bagaimana rasa syukur itu kita hayati dan warnai sepanjang perjalanan hidup.
Wallahu a’lam bi as shawab